Maqashid Syariah versi Jasser Auda
Dr. Rosidin, M.Pd.I
http://www.dialogilmu.com
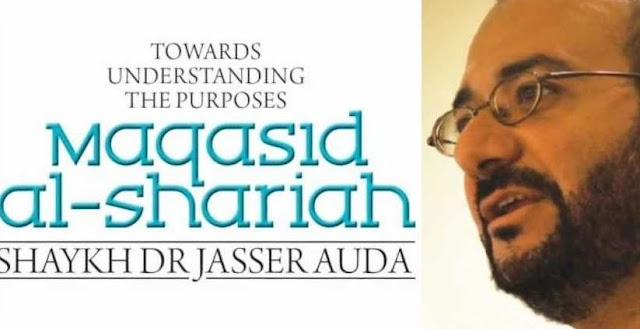 |
| Maqashid Syariah versi Jasser Auda |
Signifikansi Maqashid
Syariah tergambar dalam sebuah cerita tentang seorang putri cilik
yang pernah bertanya kepada bapaknya: “Pak, mengapa kita harus berhenti pada
rambu lalu lintas?” Menghadapi pertanyaan, yang dikiranya gampang itu, si bapak
menjawab, dengan nada menggurui, “karena lampu merah telah nyala, dan warna
merah itu berarti harus berhenti”.
Akan tetapi, si
putri itu balik bertanya: “memangnya kenapa?”, maka si bapak menjawab: “agar
tidak ditilang pak polisi”. Si putri, nampak tidak puas dengan jawaban
bapaknya, dia pun balik bertanya: “lalu, mengapa pak polisi suka menilang
orang?” Si bapak menjawab: “karena berjalan saat lampu menyala merah dapat
membahayakan orang-orang”.
Si putri malah
bertanya lagi: “tapi, mengapa?” Pada saat itu, si bapak mulai berpikir agar
menjawab saja dengan jawaban yang biasa, yaitu: “beginilah aturannya”, tetapi,
ia memutuskan untuk berlaku lebih arif menghadapi putri tercintanya itu, lalu
ia menjawab: “karena tidak boleh kita membahayakan orang lain, sukakah kamu
dibahayakan orang lain?”, maka si putri menjawab: “tidak!”.
Si bapak
melanjutkan: “demikian juga, orang lain tidak suka dibahayakan”. Nabi (SAW)
telah bersabda: “Cintailah sesama, sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri”.
Si putri balik bertanya lagi: “mengapa kita harus mencintai orang lain sebagaimana
kita mencintai diri kita sendiri?”. Si bapak berpikir sejenak sebelum menjawab:
“karena manusia semuanya adalah sama, dan kalau kamu melanjutkan tanya
“mengapa” lagi, maka saya akan menjawab: “karena Allah (SWT) itu adil, termasuk
keadilan-Nya menjadikan kita semua sama dan memiliki hak yang sama, Ia
menciptakan dunia ini berdasarkan keadilan”.
Sebenarnya, pertanyaan “mengapa” yang berturut-turut dalam
cerita ini tidak lain adalah pertanyaan tentang “apakah Maqashid (dari
rambu lalu lintas) itu?” 1 Jika dikaitkan dengan Islam, maka
disebut dengan Maqashid Syariah.
Maqashid Syariah merupakan
cabang ilmu keIslaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan, yang sulit
itu, yang diwakili oleh sebuah kata yang nampak sederhana, yaitu “mengapa?”
Berikut beberapa contoh penggunaan kata ini dalam Islam:
Mengapa seorang Muslim mendirikan shalat? Mengapa Zakat merupakan salah satu
rukun Islam? Mengapa puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam? Mengapa
seorang Muslim selalu berzikir? Mengapa berlaku baik terhadap tetangga termasuk
kewajiban dalam Islam? Mengapa meminum minuman beralkohol, walaupun sedikit,
adalah dosa besar dalam Islam? Mengapa hukuman mati telah ditetapkan bagi orang
yang memperkosa atau membunuh secara sengaja? Dalam rangka ini, Maqashid
Syariah menjelaskan hikmah di balik aturan Syariat Islam. Sebagai contoh,
salah satu hikmah di balik zakat adalah untuk “memperkokoh bangunan sosial”. 2
A.
TELAAH
DEFINITIF
Terma Maqashid
berasal dari bahasa Arab مَقَاصِدْ (maqashid),
yang merupakan bentuk jamak kata مَقْصَدْ (maqshad), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat,
tujuan, tujuan akhir. Terma itu berarti telos (dalam bahasa Yunani), finalité
(Prancis), atau Zweck (Jerman). Maqashid Syariah Islam adalah
sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum Islam. 3
Bagi
sejumlah teoretikus hukum Islam, Maqashid adalah pernyataan alternatif
untuk مَصَالِحْ (mashalih)
atau ‘kemaslahatan-kemaslahatan’.
Misalnya, ‘Abd al-Malik al-Juwaini (w. 478
H/1185 M), salah seorang kontributor paling awal terhadap teori Maqashid
menggunakan istilah al-maqashid dan al-mashalih al-‘ammah (kemaslahatan
umum) secara bergantian.
Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) mengelaborasi
klasifikasi Maqashid, yang ia masukkan ke kategori kemaslahatan mursal
(al-mashalih al-mursalah), yaitu kemaslahatan yang tidak disebut secara
langsung dalam nas Islam (al-Qur’an dan Hadis), sebagaimana akan dijelaskan
nanti.
Fakhr al-Din al-Razi (w. 606 H/1209 M) dan al-Amidi (w. 631 H/1234 M) mengikuti
terminologi al-Ghazali. Najm al-Din al-Thufi (w. 716 H/1216 M) mendefinisikan
kemaslahatan sebagai ‘apa yang memenuhi tujuan sang Pembuat Syariah (al-Syari‘),
yaitu Allah SWT.
Al-Qarafi (w. 1285 H/1868 M) mengaitkan kemaslahatan dan Maqashid
dengan ‘kaidah’ Usul Fikih yang menyatakan: “Suatu Maksud tidak sah kecuali
jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindari kemudaratan”.
Ini beberapa contoh yang menunjukkan kedekatan hubungan antara Mashlahat
dan Maqashid dalam konsepsi Usul Fikih (khususnya antara abad ke-5 dan 8
H, yaitu periode ketika teori Maqashid berkembang). 4
B.
TELAAH HISTORIS
1.
Maqashid pada Masa Sahabat
Sejarah ide tentang maksud atau tujuan
tertentu yang mendasari perintah al-Qur'an dan Sunnah dapat dilacak hingga masa
sahabat Nabi SAW
sebagaimana diriwayatkan dalam sejumlah peristiwa. Salah satu contoh populer
adalah hadis bersilsilah rawi banyak (mutawatir/mutawatir) tentang
‘shalat Ashar di Bani Quraizhah’, di mana Nabi SAW mengirim sekelompok sahabat
ke Bani Quraizhah, dan memerintahkan mereka shalat Ashar di sana. Batas waktu shalat Ashar hampir habis sebelum para Sahabat
tersebut tiba di Bani
Quraizhah.
Lalu, para sahabat terbagi menjadi pendukung dua pendapat yang berbeda:
pendapat pertama bersikukuh shalat Ashar di tempat itu, apa pun yang terjadi,
sedangkan pendapat kedua bersikukuh shalat Ashar di perjalanan (sebelum waktu
shalat Ashar habis).
Rasionalisasi di balik pendapat pertama adalah bahwa
perintah Nabi SAW itu secara tekstual meminta setiap orang untuk shalat di Bani
Quraizhah, sedangkan rasionalisasi pendapat kedua adalah ‘maksud/tujuan’
perintah Nabi adalah meminta para sahabat bergegas ke Bani Quraizhah, bukan
‘bermaksud’ menunda shalat Ashar hingga habis waktu salat.
Menurut perawi,
ketika para shahabat kemudian melaporkan cerita tersebut kepada Nabi, Nabi
meneguhkan kebenaran kedua opini para sahabat. Persetujuan (taqrir) Nabi
SAW, sebagaimana pendapat para fakih dan ulama, menunjukkan kebolehan dan
kebenaran kedua sudut pandang di atas. 5
Kejadian lain yang menunjukkan
konsekuensi lebih serius dari penerapan pendekatan ‘berbasis-Maqashid’ terhadap perintah Nabi SAW terjadi pada masa Khalifah ‘Umar RA.
Status ‘Umar dalam Islam serta konsultasinya yang terus-menerus dan luas dengan
sejumlah besar para sahabat, membuat pendapat-pendapatnya memiliki signifikansi
khusus. Dalam insiden ini, para Sahabat meminta ‘Umar mendistribusikan
tanah-tanah yang baru ‘ditaklukkan’ kaum Muslimin di Mesir dan Irak kepada
mereka sebagai bagian dari harta rampasan perang (ghanimah).
Argumen mereka didasarkan pada
ayat-ayat al-Qur'an yang secara jelas membolehkan para tentara mujahid memperoleh
ghanimah mereka. ‘Umar menolak membagi seluruh kota dan daerah kepada
para sahabat dengan mengacu pada ayat lain yang memakai ungkapan lebih umum,
yang menyatakan bahwa Allah SWT memiliki ‘maksud’ agar ‘tidak menjadikan orang
kaya mendominasi harta kekayaan’. Oleh karena itu, ‘Umar (dan para pendukung
pendapatnya) memahami ayat khusus tentang ghanimah dalam konteks Maqashid hukum khusus dalam bab itu. Maqashid yang dimaksud
adalah ‘mengurangi kesenjangan ekonomi’.
Contoh lain adalah penerapan penangguhan
hukuman atas pidana pencurian pada musim kelaparan di Madinah; serta keputusan
‘Umar RA untuk memasukkan kuda ke dalam kategori kekayaan yang wajib dizakati,
meskipun sabda Nabi SAW mengecualikan kuda. Rasionalisasi ‘Umar adalah bahwa
kuda pada masa kekhalifahannya, secara signifikan, sudah melebihi nilai unta
yang oleh Nabi dimasukkan ke dalam objek wajib zakat pada masa hidup beliau.
Dengan kata lain, ‘Umar memahami ‘maksud’ zakat dalam kaitannya sebagai bentuk
bantuan sosial yang harus dibayar oleh orang kaya untuk kepentingan orang
miskin, dengan mengesampingkan tipe kekayaan baku yang disebutkan dalam Sunnah
dan memahami Sunnah tersebut melalui implikasi literalnya (harfiah).
Namun,
‘Umar RA tidak menerapkan pendekatan berbasis-Maqashid ini pada seluruh keputusan hukum Islam. Imam Bukhari
meriwayatkan bahwa ‘Umar ditanya: “Mengapa kita masih tawaf mengelilingi Ka’bah
dengan bahu terbuka, padahal Islam sudah menang di Mekah?’. ‘Umar menjawab:
“Kita tidak akan berhenti melakukan apa pun yang sudah pernah kita lakukan pada
masa Nabi”.
Jadi, ‘Umar RA membuat perbedaan antara
ibadah (urusan peribadahan) dengan muamalah (urusan sosial kemasyarakatan), sebuah pembedaan yang didukung oleh
seluruh mazhab Usul Fikih. Al-Syathibi, misalnya, mengemukakan perbedaan ini
dalam tulisannya: ‘Pengamalan literal adalah metodologi baku pada urusan
ibadah; sedangkan pertimbangan Maqashid adalah metodologi baku pada
urusan muamalah’. 6
Ijtihad pada kasus-kasus di atas, yang
menceritakan pemahaman dan pengamalan Maqashid di era para Sahabat, memiliki signifikansi penting.
Signifikansinya adalah para Sahabat tidak selalu menerapkan ‘dalalah lafal’ (dilalah al-lafzh)—dalam istilah para pakar Usul Fikih. ‘Dalalah lafal’
berarti implikasi langsung dari suatu bunyi bahasa, dalam hal ini ‘bunyi Nas’.
Para Sahabat menerapkan implikasi praktis yang didasarkan pada ‘dalalah maksud’
(dilalah
al-maqshid). ‘Dalalah maksud’ berarti implikasi
tujuan atau niat di balik lafal tertentu. Dalalah Maksud ini memungkinkan
fleksibilitas yang lebih besar dalam memahami teks (lafzh) dan
meletakkannya dalam konteks situasi seperti contoh yang diilustrasikan di atas.
7
2.
Maqashid pada Abad Ke-3
s/d Ke-5 H
Setelah era Sahabat, teori dan
klasifikasi Maqashid mulai berkembang. Tetapi, Maqashid
sebagaimana yang kita kenal saat ini tidak berkembang dengan jelas hingga masa
para ahli Usul Fikih belakangan, yaitu pada abad ke-5 hingga 8 H. Dalam kurun waktu
tiga abad, ide maksud/sebab (hikmah, ‘illat, munasabah, atau
makna) tampak pada beberapa metode penalaran yang digunakan oleh para imam
mazhab tradisional, seperti penalaran melalui Qiyas dan Istihsan.
Tetapi, Maqashid sendiri belum menjadi subjek (topik) karya ilmiah
tersendiri atau menjadi perhatian khusus hingga akhir abad ke-3 H. Kemudian, klasifikasi
Maqashid oleh Imam al-Juwaini (w. 478 H/1085 M) terjadi lebih lama lagi,
yaitu pada abad ke-5 H. Berikut ini adalah usaha melacak konsepsi-konsepsi Maqashid
awal antara abad ke-3 dan 5 H: 8
Pertama, Al-Tirmidzi al-Hakim (w.
296 H/908 M) mendedikasikan karya terkenal pertama bagi topik Maqashid,
di mana terma Maqashid digunakan sebagai judul buku al-Shalah wa
Maqashiduha (Shalat dan Maqashid-nya). Buku ini berisi sekumpulan
hikmah dan ‘rahasia’ spiritual di balik setiap gerakan salat, dengan
kecenderungan sufi. Contohnya adalah ‘memfokuskan shalat seseorang’ sebagai Maqashid di balik menghadap Kabah.
Kedua,
Abu Zaid al-Balkhi (w. 322 H/933 M) mengemukakan karya
terkenal pertama tentang Maqashid muamalah, al-Ibanah ‘an ‘ilal al-Diyanah (Penjelasan Tujuan-tujuan di Balik Praktik-praktik Ibadah),
di mana dia menelaah Maqashid di balik hukum-hukum yuridis Islam.
Al-Balkhi juga menulis
sebuah buku khusus tentang kemaslahatan berjudul Mashalih al-Abdan wa
al-Anfus (Kemaslahatan-kemaslahatan Raga dan Jiwa); dia menjelaskan
bagaimana praktik dan hukum Islam berkontribusi terhadap kesehatan, baik fisik
maupun mental.
Ketiga, Al-Qaffal al-Kabir (w.
365 H/975 M) menulis manuskrip kuno terkait topik Maqashid, Mahasin
al-Syara’i‘ (Keindahan-keindahan Hukum Syariah). Setelah pendahuluan 20
halaman, al-Qaffal
melanjutkan dengan membagi bukunya sesuai dengan bab-bab kitab fikih tradisional.
Dia menyebutkan masing-masing hukum secara singkat dan mengelaborasi Maqashid dan hikmah di baliknya. Buku ini menandai langkah penting
dalam perkembangan teori Maqashid.
Keempat, Ibn Babawaih al-Qummi (w. 381 H/991 M). Beberapa peneliti
mengklaim bahwa penelitian tentang Maqasid Syariah terbatas pada mazhab
fikih Sunni hingga abad ke-20 M. Tetapi, monografi yang dikenal pertama kali
didedikasikan pada Maqashid sebenarnya ditulis oleh Ibn Babawaih al-Shaduq
al-Qummi, salah seorang fakih terkemuka Syiah abad ke-4 H, yang menulis buku
yang memuat 335 bab tentang subjek ini.
Buku ini berjudul ‘Ilal al-Syara’i‘ (Alasan-alasan di balik hukum Syariah),
‘merasionalisasikan’ keimanan kepada Allah SWT, kenabian, surga dan rukun iman
lainnya. Buku ini juga memberikan rasionalisasi moral terhadap shalat, puasa, haji, zakat, berbakti
kepada orangtua, dan kewajiban lain.
Kelima, Al-‘Amiri al-Failasuf (w.
381 H/991 M) mengajukan klasifikasi teoretik pertama terhadap Maqashid
dalam karyanya al-I‘lam bi Manaqib al-Islam (Pemberitahuan tentang
Kebaikan-kebaikan Islam). Tetapi, klasifikasi al-‘Amiri semata-mata berdasarkan ‘hukum pidana’
(hudud) dalam hukum Islam.
3.
Maqashid pada Abad Ke-5
s/d Ke-8 H
Abad ke-5 H menyaksikan lahirnya apa
yang disebut oleh ‘Abdullah bin Bayyah dengan filsafat hukum Islam. Metode literal dan nominal yang berkembang
hingga abad ke-5 H terbukti tidak mampu menangani kompleksitas perkembangan
peradaban. Inilah mengapa ‘kemaslahatan Mursal’ (al-Mashlahah
al-Mursalah) dikembangkan sebagai metode yang mencakup ‘apa yang tidak
disebutkan dalam Nas’, demi menutupi kekurangan metode Qiyas.
Kemaslahatan Mursal membantu mengisi kesenjangan ini dan juga mendorong
kelahiran teori Maqashid dalam hukum Islam.
Ada beberapa fakih
yang memberi kontribusi paling signifikan terhadap teori Maqashid antara
abad ke-5 hingga 8 H adalah Abu al-Ma‘ali al-Juwaini, Abu Hamid al-Ghazali,
Al-‘Izz Ibn ‘Abd al-Salam, Syihab al-Din al-Qarafi, Syams al-Dīn Ibn al-Qayyim,
serta yang paling fenomenal, Abu Ishaq al-Syathib. Berikut ini
penjelasan lebih detail tentang tokoh-tokoh tersebut: 9
Pertama, Abu al-Ma‘ali al-Juwaini
(w. 478 H/1085 M).. Karya
al-Juwaini, al-Burhan fi Ushul al-Fiqh (Dalil-dalil nyata dalam Usul Fikih)
adalah risalah Usul Fikih pertama yang memperkenalkan teori ‘tingkatan
keniscayaan’, dengan cara yang mirip dengan teori ‘tingkatan keniscayaan’ yang
familier saat ini. Dia menyarankan lima tingkatan Maqashid, yaitu keniscayaan
(dharurat), kebutuhan publik (al-hajah al-‘ammah), perilaku moral
(al-makrumat), anjuran-anjuran (al-mandubt) dan ‘apa yang tidak
dapat dicantumkan pada alasan khusus’.
Dia mengemukakan bahwa Maqashid
hukum Islam adalah kemaksuman (al-‘ishmah) atau penjagaan keimanan,
jiwa, akal, keluarga, dan harta. Karya al-Juwainī, Ghiyats al-Umam
(Penyelamat Umat-umat) juga memberi kontribusi penting terhadap teori Maqashid,
walaupun buku itu utamanya ditujukan untuk isu politik. Contoh-contoh Maqashid
dalam buku ini, di mana al-Juwaini melakukan ‘rekonstruksi’ terhadap hukum
Islam, adalah ‘kemudahan’ dalam hukum thaharah; ‘menghilangkan beban
orang miskin’ dalam hukum zakat; dan ‘suka sama suka’ dalam hukum perdagangan. Jadi,
Ghiyats al-Umam merupakan agenda untuk ‘rekonstruksi’ hukum Islam
berdasarkan Maqashid.
Kedua,
Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H/1111 M). Murid al-Juwaini, Abu Hamid al-Ghazali, mengembangkan teori gurunya lebih
jauh dalam kitabnya, al-Mustashfa (Sumber yang Dijernihkan).
Dia mengurutkan ‘kebutuhan’ yang
disarankan al-Juwaini sebagai berikut: 1) keimanan; 2) jiwa; 3) akal; 4)
keturunan; 5) harta. Al-Ghazali juga mencetuskan istilah ‘perlindungan’ (al-hifzh)
terhadap kebutuhan-kebutuhan ini. Di
samping analisis detail yang dia tawarkan, al-Ghazali amat terpengaruh oleh mazhab Syafi'i
(yang menilai Qiyas sebagai
satu-satunya metode ijtihad yang sah), menolak memberikan hujjah atau legitimasi independen bagi Maqashid atau Mashalih apa pun yang dia tawarkan.
Ketiga,
Al-‘Izz Ibn ‘Abd al-Salam (w. 660 H/1209 M). Al-‘Izz menulis dua buku tentang Maqashid, dalam nuansa ‘hikmah di balik hukum Islam’, yaitu Maqashid al-Shalah (Maqashid Shalat)
dan Maqashid
al-Shawm (Maqashid Puasa).
Tetapi, kontribusi signifikannya terhadap
perkembangan teori Maqashid adalah bukunya tentang kemaslahatan yang
berjudul Qawa‘id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam (Kaidah-kaidah Hukum bagi
Kemaslahatan Umat Manusia). Di samping investigasinya yang ekstensif tentang
konsep Mashlahah (kemaslahatan) dan Mafsadah (kemudaratan),
al-‘Izz juga menghubungkan validitas hukum dengan Maqashid-nya.
Misalnya, dia menyatakan: ‘setiap amal yang mengabaikan Maqashid-nya
adalah batal.
Keempat,
Syihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H/1285 M). Kontribusi al-Qarafi terhadap teori Maqashid adalah diferensiasi antara jenis-jenis perbuatan Nabi SAW berdasarkan ‘maksud atau niat’ beliau.
Al-Qarafi menulis dalam al-Furuq
(Perbedaan-perbedaan): “Ada perbedaan antara perbuatan-perbuatan Nabi SAW dalam
kapasitas beliau sebagai rasul yang menyampaikan wahyu, sebagai hakim, dan
sebagai pemimpin. Implikasinya dalam hukum Islam adalah apa yang beliau
sabdakan atau lakukan dalam kapasitas sebagai rasul akan menjadi hukum yang
bersifat umum dan permanen… (tetapi,) keputusan hukum yang berhubungan dengan
militer, kepercayaan publik… penunjukan hakim dan gubernur, pembagian harta
rampasan perang dan penandatanganan surat… semuanya khusus dalam kapasitas sebagai
pemimpin. Jadi, al-Qarafi mendefinisikan ‘Maqashid’ sebagai maksud/niat Nabi SAW sendiri dalam perbuatan-perbuatan
beliau. Kemudian, Ibn ‘Asyur (w. 1976 M) mengembangkan ‘diferensiasi’ al-Qarafi
di atas dan memasukkannya ke dalam definisi Maqashid versinya.
Al-Qarafi
juga menulis tentang ‘pembukaan sarana untuk meraih kemaslahatan’ (fath al-dzara’i‘),
yang juga merupakan ekspansi signifikan bagi teori Maqashid. Al-Qarafi
mengusulkan bahwa apabila sarana yang mengarahkan pada tujuan haram harus
ditutup, maka sarana yang mengarahkan pada tujuan halal seharusnya dibuka.
Kelima, Syams al-Din Ibn al-Qayyim (w. 748 H/1347 M). Kontribusi Ibn al-Qayyim terhadap teori
Maqashid adalah melalui kritiknya yang sangat
mendetail terhadap ‘trik-trik fikih’ (al-hiyal al-fiqhiyyah), berdasarkan fakta bahwa hal tersebut
bertentangan dengan Maqasid.
Ibn al-Qayyim menulis: “Trik-trik fikih adalah
aksi-aksi kejahatan yang diharamkan karena: pertama, trik-trik fikih
bertentangan dengan hikmah legislasi; dan kedua, trik-trik fikih
mengandung Maqashid yang diharamkan. Orang bermaksud melakukan riba, dia
dinilai berdosa, meskipun tampilan transaksi-palsunya kelihatan sah. Orang
tersebut tidak berniat jujur untuk melakukan transaksi sah, melainkan bermaksud
melakukan transaksi haram. Sama berdosanya, orang yang bertujuan mengubah jatah
ahli waris dengan melakukan penjualan palsu (kepada salah seorang ahli
warisnya)… Hukum Syariah itu menjadi gizi dan obat bagi kita karena hakikatnya,
bukan karena nama dan tampilan luarnya”.
Ibn
al-Qayyim meringkas metodologi yuridisnya berdasarkan ‘hikmah dan kesejahteraan
manusia’ dengan kalimat tegas berikut ini: “Syariah didasarkan pada kebijaksanaan
demi meraih keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Syariah seluruhnya
terkait dengan keadilan, kasih-sayang, kebijaksanaan dan kebaikan. Jadi, hukum
apa pun yang mengganti keadilan dengan ketidakadilan; kasih sayang dengan
kebalikannya; kemaslahatan umum dengan kejahatan; atau kebijaksanaan dengan
omong-kosong, maka hukum tersebut bukan bagian dari Syariah, meskipun diklaim
sebagai bagian dari Syariah menurut beberapa interpretasi.”
Keenam, Abu Ishaq al-Syathibi (w. 790 H/1388 M). Al-Syathibi menggunakan terminologi serupa dengan
al-Juwaini dan
al-Ghazali. Tetapi, dalam karyanya, al-Muwafaqat
fi Ushul al-Syari‘ah (Kesesuaian-kesesuaian dalam Dasar-dasar Syariah),
al-Syathibi mengembangkan teori Maqashid dalam tiga cara substansial
berikut:
a) Maqashid yang semula sebagai bagian dari ‘Kemaslahatan
Mursal’ (al-mashalih al-mursalah) menjadi bagian dari dasar-dasar hukum Islam.
Sebelum al-Muwafaqat karya al-Syathibi ini, Maqashid termasuk
dalam kategori ‘kemaslahatan-kemaslahatan lepas’, yang tidak disebutkan secara
langsung dalam Nas, dan tidak pernah dinilai sebagai dasar hukum Islam yang
mandiri.
Al-Syathibi memulai al-Muwafaqat dengan mengutip al-Qur'an demi
membuktikan bahwa Allah SWT memiliki Maqashid dalam ciptaan-Nya, dalam
pengutusan para rasul maupun dalam menentukan Hukum. Maka, al-Syathibi menilai Maqashid
sebagai ‘pokok-pokok agama (ushul al-din), kaidah-kaidah Syariah (qawa‘id
al-syari‘ah), dan keseluruhan keyakinan (kulliyyat al-millah)’;
b) Dari
‘hikmah di balik hukum’ menjadi ‘dasar bagi hukum’. Berdasarkan fondasi dan
keumuman Maqashid, al-Syathibi berpendapat bahwa ‘sifat keumuman (al-kulliyyah)
dari keniscayaan (dharuriyyat), kebutuhan (hajiyyat) dan
kelengkapan (tahsiniyyat) tidak bisa dikalahkan oleh-hukum parsial (juz’iyyat)’.
Hal ini agak berbeda dari Usul Fikih tradisional, bahkan Al-Syathibi juga
menjadikan ‘pengetahuan tentang Maqashid’ sebagai persyaratan untuk
kebenaran penalaran hukum (ijtihad) dalam seluruh levelnya;
c) Dari
‘ketidakpastian’ (zhanniyyah) menuju ‘kepastian’ (qath‘iyyah).
Dalam rangka mendukung status baru yang dia berikan kepada Maqashid di
kalangan para pakar Usul Fikih, al-Syathibi memulai karyanya tentang Maqashid
dengan membuktikan ‘kepastian’ proses induktif yang dia gunakan untuk
menyimpulkan Maqashid, yang didasarkan pada sejumlah besar dalil yang
dia pertimbangkan.
Buku al-Syathibi ini menjadi buku standar Maqasid Syariah di
kalangan ulama hingga abad ke-20 M; namun usulan al-Syathibi untuk menjadikan Maqashid
sebagai pokok-pokok Syariah (Ushul Syariah), seperti disarankan judul
bukunya, tidak diterima secara luas.
4.
Maqashid pada Abad
Ke-20 H
Selanjutnya
pada era kontemporer ini, konsep
Maqashid Syariah tersebut mengalami
pergeseran, dari ‘penjagaan’ dan ‘perlindungan’ menuju ‘pengembangan’ dan
‘hak-hak asasi’. Pergeseran ini merupakan kontribusi Ibn ‘Asyur yang membuka
pintu bagi para cendekiawan kontemporer untuk mengembangkan teori Maqashid
dalam pelbagai cara baru. Orientasi pandangan yang baru itu bukanlah konsep
perlindungan (hifzh) versi al-Ghazali, melainkan konsep ‘nilai’ dan
‘sistem’ versi Ibn
‘Asyur. Berikut ini penjelasan lebih detailnya: 10
Pertama, Hifzh
al-Din (perlindungan
agama). Dahulu
bermakna ‘hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar’ versi al-‘Amiri.
Namun, akhir-akhir ini bergeser menjadi ‘kebebasan kepercayaan’ (freedom of
faiths) versi Ibn ‘Asyur atau ‘kebebasan berkeyakinan’ dalam
ungkapan kontemporer lain. Para penganjur pandangan ini sering mengutip ayat
al-Qur'an: ‘tiada paksaan dalam agama’ sebagai prinsip fundamental, alih-alih memahaminya sebagaimana pandangan
populer dan tidak akurat, yaitu menyerukan ‘hukuman bagi kemurtadan’ (hadd
al-riddah).
Kedua, Hifzh
al-Nafs (perlindungan jiwa
raga) dan Hifzh al-‘Irdh (perlindungan
kehormatan). Semula berkisar pada penjagaan jiwa-raga dan harga diri, namun
akhir-akhir ini berangsur-angsur diganti oleh ‘perlindungan harkat dan martabat
manusia’, bahkan ‘perlindungan hak-hak asasi manusia’.
Ketiga, Hifzh
al-‘Aql (perlindungan akal).
Jika selama ini masih terbatas pada larangan minum minuman keras, sekarang
berkembang menjadi ‘pengembangan pikiran ilmiah’, ‘perjalanan menuntut ilmu’,
‘melawan mentalitas taklid’, dan ‘mencegah mengalirnya tenaga ahli ke luar negeri’.
Keempat, Hifzh al-Nasl (perlindungan keturunan). Pada abad
ke-20 para pakar Maqashid secara signifikan mengembangkan ‘perlindungan
keturunan’ menjadi teori berorientasi keluarga, misalnya ‘peduli keluarga’.
Kelima, Hifzh
al-Mal (perlindungan
harta). Jika semula bermakna ‘hukuman bagi
pencurian’ versi al-‘Amiri dan ‘proteksi uang’ versi al-Juwaini, akhir-akhir
ini berkembang menjadi istilah-istilah sosio-ekonomi yang familier, misalnya
‘bantuan sosial’, ‘pengembangan ekonomi’, ‘distribusi uang’, ‘masyarakat
sejahtera’ dan ‘pengurangan perbedaan antar-kelas sosial-ekonomi’. Pengembangan
ini memungkinkan penggunaan Maqashid untuk mendorong pengembangan
ekonomi, yang sangat dibutuhkan di kebanyakan negara-negara berpenduduk
mayoritas Muslim.
C.
TELAAH TEORETIS
Klasifikasi
klasik Maqashid Syariah meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan, yaitu: al-Dharuriyyat
(Keniscayaan), al-Hajiyyat (Kebutuhan), dan al-Tahsiniyyat
(kemewahan). Kemudian, para ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima): Hifzh
al-Din (pelestarian agama), Hifzh al-Nafs (pelestarian jiwa-raga),
Hifzh al-‘Aql (pelestarian akal), Hifzh al-Nasl (pelestarian
keluarga atau keturunan) dan Hifzh al-Mal (pelestarian harta). Sebagian ulama menambah Hifzh al-‘Irdh
(pelestarian kehormatan atau harga diri). Berikut ini visualisasi klasifikasi Maqashid
Syariah: 11
 |
| Klasifikasi Maqashid Syariah |
1.
Dharuriyyat
Melestarikan
kelima (atau keenam) Maqashid Syariah yang tergolong Dharuriyyat adalah
sebuah keniscayaan, yang tidak bisa tidak ada, jika kehidupan manusia
dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang. Kehidupan manuia akan manghadapi
bahaya jika akal mereka terganggu, oleh karena itu Islam melarang keras khamar,
narkoba dan sejenisnya.
Kehidupan manusia akan berada dalam keadaan bahaya jika
nyawa mereka tidak dijaga dan dilestarikan dengan berbagai tindakan pencegahan
penyakit dan/atau jika tidak tersedia sistem penjaminan lingkungan dari polusi,
maka, dalam rangka inilah kita dapat memahami pelarangan Nabi (SAW) akan
penyiksaan terhadap manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.
Keberlangsungan
hidup manusia akan terancam, juga, apabila terjadi krisis ekonomi yang
menyeluruh, oleh karenanya, Islam melarang sebab-musabab terjadinya krisis
tersebut seperti monopoli, riba, korupsi dan kecurangan. Demikian pula dengan
pelestarian keturunan, yang didudukkan pada martabat yang tinggi oleh Islam,
dimana terapat hukum-hukum untuk mendidik dan memilihara anak-anak serta
menjaga keutuhan keluarga (seperti pelarangan zina, durhaka terhadap orang tua
dan melantarkan anak atau tidak berlaku adil kepadanya).
Adapun pelestarian
agama, yang merupakan kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia,
khususnya kehidupan akherat. Demikian pula, terdapat konsensus antar pengikut
agama samawi yang lain bahwa maksud-maksud pokok tersebut adalah tujuan akhir
dari segenap arahan agama, dan bukan hanya agama Islam. 12
Masing-masing Maqashid
Syariah tersebut memiliki dua konteks, yaitu proaktif dan protektif.
Proaktif berarti usaha untuk mewujudkan, mengokohkan atau mengembangkan,
sedangkan protektif berarti usaha untuk menjaga atau mempertahankan. Berikut
pemaparan lebih jelasnya:
Pertama, Hifzh al-Din (Pelestarian
Agama). Dalam konteks
proaktif, Allah SWT mewajibkan umat muslim agar melaksanakan rukun Islam. Dalam
konteks protektif, Allah SWT melarang kemusyrikan, kekafiran, kemurtadan,
kemunafikan hingga kefasikan.
Kedua, Hifzh al-Nafs (Pelestarian
Jiwa-Raga). Dalam konteks proaktif, Allah SWT memerintahkan makan,
minum, berpakaian dan berolahraga untuk kesehatan jasmani dan ruhani. Dalam
konteks protektif, Allah SWT melarang pembunuhan dengan sengaja, bunuh diri,
pertengkaran hingga melukai orang lain.
Ketiga, Hifzh al-‘Aql (Pelestarian
Akal). Dalam konteks proaktif, Allah SWT memerintahkan
aktivitas belajar-mengajar yang berfungsi untuk mengembangkan akal dengan ilmu
pengetahuan. Dalam konteks protektif, Allah SWT melarang manusia untuk
mengonsumsi makanan dan minuman yang dapat merusak atau melemahkan kemampuan
otak, misalnya mengonsumsi narkotika. Bahkan pelakunya akan mendapatkan hukuman
yang berat.
Keempat, Hifzh al-Nasl (Pelestarian
Keluarga atau Keturunan). Dalam konteks proaktif, Allah SWT mensyariahkan
pernikahan agar manusia terus menerus berkembang-biak. Dalam konteks protektif,
Allah SWT melarang perzinahan [termasuk pacaran], tuduhan zina, hubungan sesama
jenis, dan lain-lain.
Kelima, Hifzh al-Mal (Pelestarian
Harta). Dalam kontotasi proaktif, Allah SWT memerintahkan
bekerja mencari nafkah yang halal, mensyariahkan berbagai akad muamalah yang
halal, seperti jual beli. Dalam konteks protektif, Allah SWT melarang pencurian
[termasuk korupsi], perampokan, praktik riba dan akad-akad yang mengandung
penipuan.
Berikut ini tabel yang memuat
contoh-contoh Maqashid Syariah dalam konteks proaktif maupun protektif:
Contoh-Contoh Maqashid Syariah
|
MAQASHID SYARIAH
|
KONTEKS PROAKTIF
[Perintah, Anjuran]
|
KONTEKS PROTEKTIF
[Larangan, Ancaman]
|
|
Hifzh
al-Din (Pelestarian Agama)
|
Ø Shalat
Ø Membaca al-Qur’an
|
Ø Meninggalkan shalat
Ø Percaya horoskop
|
|
Hifzh
al-Nafs (Pelestarian Jiwa-Raga)
|
Ø Olahraga
Ø Makanan bergizi
|
Ø Merokok
Ø Berkelahi
|
|
Hifzh
al-‘Aql (Pelestarian Akal)
|
Ø Membaca-Menulis
Ø Penelitian
|
Ø Mengonsumsi narkoba
Ø Menyontek
|
|
Hifzh
al-Nasl (Pelestarian Keluarga)
|
Ø Menikah
Ø Silaturrahim
|
Ø Berpacaran
Ø Berzina
|
|
Hifzh
al-Mal (Pelestarian Harta)
|
Ø Bekerja
Ø Menabung
|
Ø Pengangguran
Ø Korupsi
|
2.
Hajiyyat
Selanjutnya tujuan-tujuan yang termasuk golongan kebutuhan (al-Hajiyyat). Tujuan-tujuan dalam golongan ini merupakan
kurang-niscaya bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Menikah, berdagang, dan
sarana transportasi adalah contoh kebutuhan. Islam mendorong pengikutnya untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu dan mengaturnya. Ketidaksediaan
kebutuhan-kebutuhan itu, khususnya pada tingkat individu, bukanlah soal hidup
mati.
Misalnya, jika sebagian manusia memutuskan untuk tidak menikah, atau jika
sebagian di antaranya memutuskan untuk tidak berdagang, maka kehidupan manusia
tidak akan terancam. Akan tetapi, apabila salah satu kebutuhan itu tidak
tersedia bagi sebagian besar manusia, maka ia akan berpindah dari jenjang
‘kebutuhan’ ke ‘keniscayaan’. Dalam rangka inilah kita dapat memahami kaidah
yang berbunyi:
اَلْحَاجَةُ إِذَا عَامَّتْ، نَزَلَتْ مَنْزِلَةَ
الضَّرُوْرَةِ
Sebuah kebutuhan jika menjadi umum, maka ia
sudah pantas untuk didudukkan pada jenjang keniscayaan. 13
3.
Tahsiniyyat
Adapun al-Tahsiniyyat (kemewahan),
yang memperindah kehidupan, seperti minyak wangi, pakaian yang menarik, rumah yang asri. Islam mendukung adanya
hal-hal itu dan menganggapnya sebagai tanda kemurahan Allah (SWT) terhadap
manusia dan rahmat-Nya yang tak terbatas.
Akan tetapi, Islam
tidak menghendaki agar mausia memberi perhatian terhadap golongan yang terakhir
ini (al-Tahsinyyat) yang melebihi perhatiannya terhadap kedua
golongan sebelumnya (al-Dharuriyyat dan al-Hajiyyat). 14
Terdapat hubungan
persimpangan dan keterkaitan
antar jenjang Maqashid Syariah tersebut.
Persimpangan dan keterkaitan itulah yang telah lama dicatat oleh Imam al-Syathibi.
Pernikahan dan perdagangan, misalnya, yang merupakan kebutuhan, memiliki
hubungan manfaat yang terkait erat dengan pelestarian keturunan dan harta, yang
termasuk golongan keniscayaan. Contoh-contoh yang menjelaskan persimpangan dan
keterkaitan antar Maqashid Syariah adalah sangat banyak, dimana
kekurangan besar pada sebuah jenjang yang lebih rendah, menaikkan
klasifikasinya kepada jenjang yang lebih atas.
Misalnya, jika perdagangan
mengalami resesi (kemunduran) pada tingkatan internasional, maka keadaan ini
memindahkan perdagangan dari jenjang kebutuhan kepada jenjang keniscayaan. Oleh
karena itu, para fakih Muslim lebih cenderung untuk memandang Maqashid
Syariah pada jenjang keniscayaan sebagai lingkaran-lingkaran yang saling
berjalin, ketimbang piramida hirarkis. 15
Catatan Kaki
1 Jasser Auda, al-Maqasid
untuk Pemula. Terjm. Ali ‘Abdelmon’im. (Yogyakarta: UIN-Suka Press,
2012), h. 1.
2 Jasser Auda, al-Maqasid
untuk Pemula, h. 2-3.
3 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam
melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem. Terj. Rosidin dan Ali Moen’im.
(Bandung: Mizan, 2015), h. 32-33.
4 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam
melalui Maqasid Syariah, h. 33.
5 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam
melalui Maqasid Syariah, h. 41.
6 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam
melalui Maqasid Syariah, h. 41-44.
7 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam
melalui Maqasid Syariah, h. 44.
8 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam
melalui Maqasid Syariah, h. 45-49.
9 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam
melalui Maqasid Syariah, h. 50-56.
10 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam
melalui Maqasid Syariah, h. 56-60.
11 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam
melalui Maqasid Syariah, h. 35.
12 Jasser Auda, al-Maqasid
untuk Pemula, h. 5-6.
13 Jasser Auda, al-Maqasid
untuk Pemula, h. 6.
14 Jasser Auda, al-Maqasid
untuk Pemula, h. 6.
15 Jasser Auda, al-Maqasid
untuk Pemula, h. 6-7.
